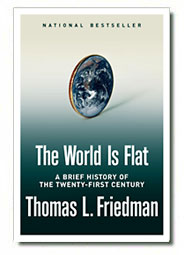Havel,
Pada 1989, ketika menginjak usia 46 tahun, Marsillam Simanjuntak mempertahankan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Judulnya: Unsur Hegelian dalam Pandangan Negara Integralistik. Niscaya, ini bukan skripsi formalitas, yang dibikin sekadar agar bisa keluar kampus dengan menenteng status sarjana. Kata beberapa orang, mutunya tak kalah dengan disertasi.
Lima tahun kemudian, dengan sejumlah revisi di sana-sini, skripsi tersebut diterbitkan. Judulnya lebih singkat: Pandangan Negara Integralistik. Dua nama begitu kerap disebut di buku itu: Georg W.F. Hegel dan Supomo. Pemilik nama pertama ditengarai sangat memengaruhi si empunya nama kedua. Itu terbaca dalam proses penyusunan UUD 1945, yang juga melibatkan Supomo dan bapak bangsa lain.
Dari benak Supomo, meluncurlah pandangan negara integralistik: negara dan rakyat tak terpisahkan, keduanya memiliki kepentingan yang identik—lantaran itu, mustahil negara menindas rakyat. Maka, enyahlah individualisme dan liberalisme!
Ada Hatta yang menentang pandangan Supomo. Putra Minang itu menyerukan unsur-unsur kedaulatan rakyat. Dan, inilah ujung persabungan ide: Supomo kalah, tafsirnya masuk tong sampah sejarah. Namun, ketika Marsillam menulis karya itu, tafsir tersebut telah dimunculkan lagi ke permukaan. Dan, praktik politik Orde Baru mengafirmasinya.
Marsillam sendiri adalah salah seorang seteru Orde Baru. Gara-gara Malari, ia pernah masuk bui. Jika ingatanku tak berkhianat, saat itu ia bekerja sebagai dokter di Garuda Indonesia. Lepas dari penjara, aktivis 66 ini kembali ke Garuda. Tapi, akibat emoh mengikuti penataran P4, ia mesti hengkang.
Sedikit saja informasi yang aku miliki tentang Marsillam. Aku cuma pernah dengar, teman Gus Dur sejak kecil ini punya keluasan wawasan dan sangat kuat berlogika. Jangan berani menantang berdiskusi jika tak siap dengan segudang “amunisi.” Lalu, bahwa halak hita ini punya integritas, susah diajak kompromi. Ketika para politisi di Senayan tak meloloskannya sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa tahun lalu, seorang teman berkata, “Duh, para koruptor pasti lega….”
Saat Pandangan Negara Integralistik terbit, arwah Supomo mungkin gerah di alam kubur. Kini, sejumlah kalangan gusar menyaksikan Marsillam masuk (lagi) ke lingkaran dalam istana.